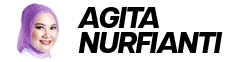Analisis Kritis terhadap Arah Kebijakan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Indonesia
Dalam sebuah diskusi formal RDPU BULD DPD RI yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, seorang narasumber ahli, Dr. Halilul Khairi, M.Si. menyampaikan Paparan mendalam mengenai problematika tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.
Paparan diawali dengan informasi mengenai mandeknya pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Desa, yang secara substansial telah mencapai kesepakatan 100%, namun terhambat selama hampir satu tahun akibat rivalitas institusional antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) dengan Kemendagri dalam menjembatani kewenangan.
Hambatan ini, menurutnya, merefleksikan patologi birokrasi yang lebih mementingkan ekspansi kekuasaan institusional—sejalan dengan Hukum Parkinson yang mengarah pada tendensi money maximizer—daripada kemajuan rakyat.
Paradigma Penguatan Desa: Elit versus Komunitas
Narasumber mengajukan pertanyaan fundamental: siapa subjek yang sesungguhnya hendak diperkuat dalam kebijakan desa? Apakah desa sebagai entitas komunitas, perangkat desa, atau kepala desa?
Analisisnya menunjukkan bahwa kebijakan saat ini cenderung memperkuat elit desa, yakni pemerintah desa.
Hal ini tecermin dari tuntutan dan realisasi kebijakan seperti perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades) menjadi delapan tahun dan peningkatan remunerasi.
Pendekatan ini dinilai keliru karena mengabaikan esensi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum tradisional yang memiliki hak mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Otonomi desa yang bermakna seharusnya memberikan ruang luas bagi komunitas untuk mengatur dirinya, bukan sekadar memperkuat aparatur pemerintahannya.
Ketika fokus hanya pada dana desa dan penguatan pemerintah desa tanpa diimbangi dengan penguatan komunitas, terjadi ketimpangan kekuasaan. Pemerintah desa menjadi kuat dengan dana besar, sementara masyarakatnya lemah.
Kondisi ini menciptakan potensi korupsi yang tinggi karena lemahnya kontrol sosial dan politik dari masyarakat.
Inefektivitas Pengawasan Formal dan Urgensi Kontrol Publik
Sistem pengawasan yang ada saat ini dinilai tidak efektif untuk mencegah korupsi di tingkat desa. Pengawasan dari pemerintah pusat terhadap lebih dari 76.000 desa dianggap mustahil secara praktis.
Demikian pula, pengawasan fungsional yang bersifat elitis oleh berbagai lembaga—mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Irjen) di kementerian, Satuan Pengawas Internal (SPI) di universitas, hingga inspektorat di tingkat provinsi dan kabupaten—terbukti memiliki kelemahan inheren.
Lembaga-lembaga ini rentan terhadap praktik exchange and bargaining (pertukaran dan tawar-menawar), sehingga tidak memberikan efek jera yang signifikan. Narasumber menganalogikan penindakan korupsi saat ini seperti buaya di sungai yang hanya memangsa sebagian kecil dari ribuan hewan yang menyeberang; jumlah pelaku yang ditindak tidak sebanding dengan masifnya praktik korupsi yang terjadi.
Sebagai solusi, ditekankan bahwa mekanisme kontrol yang paling kuat dan efektif adalah kontrol publik. Kontrol ini memiliki keunggulan karena melibatkan banyak orang, tidak memerlukan surat tugas atau biaya operasional, dan selalu hadir di lokasi.
Untuk mengaktifkan kontrol publik, dua syarat utama harus dipenuhi: pertama, memberikan ruang akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap data dan informasi pemerintahan desa; kedua, menyediakan saluran yang jelas bagi masyarakat untuk menindaklanjuti temuan mereka.
Studi Kasus dan Model Tata Kelola Berbasis Transparansi
Sebagai bukti empiris, narasumber memaparkan studi kasus dari desanya di Pungkulo, yang berhasil mengelola “kebun desa” seluas 25 hektare dengan pendapatan tahunan lebih dari Rp1,5 miliar selama 25 tahun tanpa satu pun kasus korupsi atau pengaduan.
Kunci keberhasilannya terletak pada mekanisme tradisional yang sangat transparan.
- Dana yang masuk dikelola oleh rekening kelompok pengurus dan hanya dapat dicairkan atas persetujuan sidang masyarakat yang diadakan setiap hari Jumat di masjid.
- Perencanaan, seperti pembangunan masjid, dibahas secara terbuka.
- Faktur pembelian barang ditempel di papan pengumuman masjid, dan realisasi belanja dapat diverifikasi oleh seluruh warga.
Model sederhana berbasis rakyat ini kontras dengan model “modern” yang menerapkan sistem akuntansi kompleks seperti accrual basis, namun justru sarat dengan korupsi, konflik, dan kerumitan yang tidak perlu.
Kelemahan Sistemik dalam Proses Kebijakan dan Rekomendasi
Kelemahan fundamental dalam sistem kebijakan nasional diidentifikasi pada tumpang tindihnya peran antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Di Indonesia, direktorat jenderal yang merancang peraturan sering kali merupakan pihak yang sama yang melaksanakannya.
Praktik ini, berbeda dengan di Singapura yang memiliki statutory board terpisah, membuka ruang bagi penyusunan regulasi yang melayani kepentingan birokrasi itu sendiri, sejalan dengan “tiga nafsu kekuasaan”: berkuasa selama mungkin, semudah mungkin, dan sepenuh mungkin.
Akibatnya, regulasi yang dihasilkan cenderung rumit tanpa tujuan yang jelas (ribet tanpa tujuan) dan lebih berorientasi pada penguatan elit daripada pemberdayaan rakyat.
Oleh karena itu, direkomendasikan agar lembaga legislatif seperti DPR dan DPD, yang tidak memiliki kepentingan implementasi, melakukan peninjauan kritis terhadap peraturan pemerintah (PP) terkait desa.
Tujuannya adalah untuk memastikan apakah regulasi tersebut benar-benar memfasilitasi kemandirian desa berbasis rakyat atau justru melanggengkan struktur yang elitis. Strategi pemecahan masalah harus didasarkan pada pemetaan teori yang sistematis dan komprehensif, dari identifikasi akar masalah hingga solusi, bukan pendekatan ad-hoc (tiba waktu tiba akal).
Tata kelola keuangan desa seharusnya dapat dibuat sederhana, akuntabel, dan tertelusur, sebagaimana prinsip dasar akuntansi yakni pencatatan yang transparan, untuk mewujudkan desa yang maju, modern, dan akuntabel.