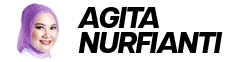Dalam sebuah forum diskusi yang berfokus pada penguatan peran tenaga ahli dan komunikasi publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Yulianti Susilo, M.A., seorang akademisi, praktisi, dan profesional di bidang penguatan kapasitas kelembagaan dari Universitas Indonesia, menyampaikan analisis mendalam mengenai tantangan dan strategi parlemen di abad ke-21. Paparan beliau, yang didasarkan pada pengalaman profesional yang luas, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi DPD RI. Pengalaman tersebut mencakup keterlibatan dalam pengembangan forum multi-stakeholder di 20 provinsi bersama IFES sejak era awal reformasi pada tahun 2000, perannya sebagai pelatih bagi tenaga ahli DPR bersama NDI, serta kontribusinya dalam program reformasi parlemen melalui Democratic Reform Support Program (DRSP) dari USAID, di mana beliau secara khusus dipercayakan di Badan Kehormatan DPR RI sekitar tahun 2010. Selain itu, beliau juga pernah menjadi konsultan di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu dan OECD untuk memperkuat koordinasi kebijakan publik lintas sektor.
Dr. Yulianti mengawali paparannya dengan menegaskan bahwa parlemen merupakan jantung dari demokrasi yang sehat. Fungsi esensial parlemen dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan merepresentasikan suara rakyat hanya dapat berjalan optimal melalui keterbukaan, transparansi, dan akses publik yang luas. Beliau menekankan bahwa anggota parlemen, sebagai representasi pilihan rakyat, memiliki kewajiban untuk membangun dan memelihara hubungan yang kuat dan terhubung secara kontinu dengan konstituennya. Hubungan yang terjaga dengan baik memastikan aspirasi rakyat dapat terwakili secara otentik, yang pada gilirannya akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran. Untuk mengkonseptualisasikan tingkat keterlibatan publik, Dr. Yulianti memperkenalkan kerangka teoretis “Tangga Partisipasi Warga” (Ladder of Citizen Participation) dari Sherry Arnstein. Kerangka ini mengklasifikasikan partisipasi ke dalam tiga tingkatan utama. Tingkat terendah adalah Non-Partisipasi, yang mencakup manipulasi dan terapi, di mana warga hanya dijadikan alat legitimasi tanpa pengaruh nyata. Tingkat menengah adalah Tokenisme, yang terdiri dari pemberian informasi, konsultasi, dan placation(penenangan), di mana warga diberi ruang untuk bersuara namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemegang kekuasaan. Tingkat tertinggi, dan yang paling ideal, adalah Kekuatan Warga (Citizen Power), yang mencakup kemitraan (partnership), pendelegasian wewenang (delegated power), dan kontrol warga (citizen control), di mana warga duduk sejajar dengan pembuat kebijakan dan memiliki kekuatan nyata untuk mempengaruhi hasil. Peningkatan partisipasi menuju jenjang tertinggi merupakan indikator vital dari pendewasaan demokrasi.
Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, Dr. Yulianti menguraikan strategi spesifik bagi DPD RI untuk menjadikan partisipasi publik sebagai inti dari kinerjanya. Strategi utama meliputi pemanfaatan teknologi digital untuk e-participation, pembangunan kanal aduan yang responsif, dan kolaborasi multi-level dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah (Pemda), organisasi masyarakat sipil (CSO), akademisi, dan media. Di sisi lain, beliau juga mengidentifikasi tantangan signifikan yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman publik mengenai fungsi dan kewenangan DPD RI yang berbeda dari DPR, hambatan struktural dan politik, serta kesenjangan digital di berbagai daerah. Sebagai ilustrasi pentingnya dukungan kelembagaan yang kuat, beliau membagikan pengalaman saat mendampingi pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dalam kunjungan ke Kongres Amerika Serikat pada tahun 2008. Pengalaman tersebut menyoroti bagaimana seorang anggota kongres, Representative David Price, didukung oleh 22 staf ahli dengan spesialisasi yang sangat beragam, mulai dari ahli nuklir hingga ahli kawasan Asia Tenggara. Hal ini sangat kontras dengan kondisi DPR RI pada tahun 2008 yang hanya memiliki satu atau dua tenaga ahli. Pengalaman ini menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap keahlian teknis sebagai fondasi kinerja legislatif yang kuat, di mana tenaga ahli tersebut mampu memberikan briefing mendalam kepada anggota dewan hingga memahami perkembangan di Indonesia secara detail. Praktik ini menjadi sebuah contoh terbaik yang relevan untuk diadopsi sesuai konteks di Indonesia.
Fokus utama dari paparan ini adalah peran strategis tenaga ahli (TA). Dr. Yulianti menekankan bahwa TA memiliki kewajiban untuk secara proaktif memantau isu-isu lokal di daerah pemilihan (dapil) anggotanya, misalnya dengan menjadikan rutinitas untuk menganalisis berita lokal setiap pagi sebagai hal pertama yang dilakukan. Hasil analisis ini harus diolah menjadi briefing singkat yang membekali anggota dewan dengan informasi relevan dan terkini, sehingga siap merespons isu yang berkembang secara mendadak. Lebih lanjut, beliau menyajikan panduan praktis untuk membangun strategi komunikasi publik yang efektif. Langkah pertama yang krusial adalah pemetaan audiens dan pemangku kepentingan (stakeholder mapping). TA harus mampu mengidentifikasi profil demografis, minat, serta kanal media yang diakses oleh berbagai kelompok masyarakat di dapil, seperti pemuda, lansia, kelompok perempuan, petani, atau seniman. Dr. Yulianti juga menyebutkan sumber informasi seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) yang menyediakan banyak publikasi dan panduan. Data untuk pemetaan ini dapat diperoleh dari sumber publik seperti Badan Pusat Statistik (BPS), data pemerintah daerah, riset NGO, maupun riset yang dilakukan secara internal atau bekerja sama dengan universitas lokal.
Setelah audiens dipetakan, TA dapat merancang strategi komunikasi yang tepat sasaran, termasuk melalui media sosial. Beliau menyediakan daftar periksa (checklist) untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kampanye media sosial. Ditekankan bahwa konten harus relevan, mendorong interaksi dua arah, dan dikelola secara konsisten. Beliau mencontohkan praktik baik dari Prof. Rhenald Kasali yang selalu memancing diskusi dengan mengajukan pertanyaan kepada audiensnya di akhir unggahan, seperti “menurut Bapak dan Ibu apa?” untuk mendorong partisipasi aktif. Selain itu, TA juga harus memiliki strategi dalam merespons berbagai jenis umpan balik dari publik, baik yang positif, negatif, maupun berupa pertanyaan, dengan berpegang pada prinsip transparansi dan kejujuran, bahkan jika itu berarti mengakui belum memiliki jawaban pada saat itu.
Sebagai kesimpulan, Dr. Yulianti menegaskan bahwa DPD RI, dalam perannya sebagai jembatan antara pusat dan daerah, harus menjadi lembaga yang lebih terbuka, inklusif, dan responsif. Keberhasilan peran ini sangat bergantung pada dukungan kelembagaan yang kuat, terutama kapasitas sumber daya manusia, yakni para tenaga ahli. Optimalisasi demokrasi digital juga akan memperluas partisipasi masyarakat daerah. Beliau mengemukakan sebuah metafora kuat untuk menggambarkan peran ini: jika parlemen adalah panggung demokrasi, maka tenaga ahli adalah sutradara yang bekerja di balik layar. Kinerja anggota dewan di atas panggung tidak akan berjalan dengan baik tanpa fondasi kerja yang kokoh dari para TA. Peran TA bukan sekadar mendukung pekerjaan administratif, melainkan memastikan suara rakyat benar-benar hadir dan dipertimbangkan dalam setiap proses kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan proaktivitas tenaga ahli merupakan investasi strategis untuk penguatan demokrasi dan legitimasi DPD RI di mata publik.