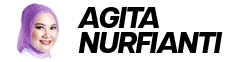Sebuah pertemuan yang diinisiasi oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Jawa Barat, Agita Nurfianti, telah diselenggarakan dengan tujuan melakukan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diskusi ini melibatkan partisipasi dari instansi-instansi kunci, termasuk Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) yang diwakili oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Laporan ini menyajikan analisis terintegrasi dari data, mekanisme penanganan, tantangan, dan kendala sistemik yang dipaparkan oleh para narasumber, dengan fokus pada isu-isu krusial seperti kekerasan, perkawinan anak, eksploitasi, dan prosedur adopsi di wilayah Jawa Barat.
Konteks Demografi, Administratif, dan Pendidikan Anak
Provinsi Jawa Barat memiliki populasi anak yang sangat signifikan, mencapai sekitar 15 juta jiwa atau 29% dari total penduduk provinsi yang telah melebihi 50 juta jiwa. Skala demografis ini menggarisbawahi urgensi dan kompleksitas tantangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dari aspek administrasi kependudukan, data per tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan akta kelahiran telah mencapai 93,95%. Meskipun angka ini tergolong tinggi, masih terdapat sekitar 6% anak yang belum memiliki dokumen fundamental tersebut. Kendala yang teridentifikasi mencakup rendahnya kesadaran masyarakat, kesulitan akses geografis di beberapa wilayah terpencil, serta isu pernikahan yang tidak tercatat secara hukum (nikah siri). Namun, telah ditegaskan bahwa regulasi saat ini memungkinkan penerbitan akta kelahiran bagi anak dari pernikahan tidak tercatat atau kehamilan tidak diinginkan dengan hanya mencantumkan nama ibu, sebuah kebijakan yang sosialisasinya perlu terus ditingkatkan untuk mengatasi hambatan administratif di tingkat masyarakat dan birokrasi. Di sektor pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) menunjukkan angka yang sangat tinggi, yaitu 99,34%. Namun, terdapat tren penurunan partisipasi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SMP. Meskipun program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah meniadakan biaya sekolah formal, faktor sosial-ekonomi dan kesadaran masyarakat masih menjadi kendala utama. Praktik menikahkan anak pada usia dini, misalnya, secara langsung memutus akses anak terhadap pendidikan dan memicu siklus permasalahan sosial yang baru dan lebih kompleks.
Analisis Isu-Isu Krusial Perlindungan Anak
Prevalensi dan Karakteristik Kekerasan Terhadap Anak
Isu kekerasan terhadap anak menjadi sorotan utama dalam diskusi. Data survei nasional menunjukkan prevalensi yang mengkhawatirkan, di mana 51,78% anak perempuan dan 49,4% anak laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau psikis. Jenis kekerasan yang paling umum terjadi adalah kekerasan emosional atau psikis, namun bentuk kekerasan ini sering kali tidak dianggap sebagai masalah serius akibat adanya normalisasi dalam pola pengasuhan di masyarakat. Sebuah paradoks teridentifikasi pada data pelaporan kasus di Jawa Barat. Meskipun survei mengindikasikan kekerasan psikis sebagai yang paling prevalen, kasus yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran dan urgensi masyarakat untuk melapor lebih terpicu oleh kekerasan yang bersifat fisik dan seksual. Data kasus yang dilaporkan menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, dengan angka mencapai 3.150 kasus perempuan dan anak pada data terkini, yang merupakan angka tertinggi di Indonesia. Peningkatan ini, meskipun tampak negatif, dapat diinterpretasikan sebagai “keberhasilan dalam tanda kutip” dari upaya sosialisasi untuk mendorong korban berani melapor (dare to speak up) dan meningkatnya ketersediaan layanan. Fenomena ini didukung oleh fakta bahwa kota-kota dengan layanan penanganan yang baik dan mudah diakses seperti Bandung, Bekasi, dan Depok justru mencatatkan jumlah kasus tertinggi. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa lebih dari 50% kasus kekerasan terjadi di lingkungan domestik atau ranah personal, dengan pelaku merupakan orang terdekat korban seperti keluarga, teman, atau pacar. Dari sisi penegakan hukum, proses pembuktian kekerasan psikis menjadi tantangan utama karena ketiadaan bukti fisik. Meskipun terdapat instrumen seperti visum et repertum psikiatrikum dari psikolog, perbedaan persepsi di antara aparat penegak hukum mengenai validitas bukti ini menjadi kendala tambahan. Data statistik menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan psikis yang dilaporkan: pada anak, jumlah kasus meningkat dari 178 pada tahun 2022 menjadi 375 pada tahun 2024, sementara pada perempuan mencapai 453 kasus pada tahun 2024. Angka ini diyakini merupakan fenomena gunung es, sehingga intervensi yang paling krusial saat ini adalah pendampingan psikologis jangka panjang untuk pemulihan korban.
Fenomena Perkawinan Anak
Perkawinan anak tetap menjadi isu signifikan di Jawa Barat, sebagaimana tercermin dari data permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama. Meskipun terjadi penurunan dari sekitar 9.000 usulan pada tahun 2023, angka permohonan dispensasi masih tinggi, mencapai 3.631 usulan dalam periode berjalan. Analisis motivasi menunjukkan bahwa faktor utama bukanlah ekonomi (0,4%), melainkan “cinta” atau hubungan emosional antar anak (82,4%), diikuti oleh kehamilan di luar nikah (13,91%). Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi harus difokuskan pada edukasi remaja dan penguatan keluarga. Sebagai respons, pemerintah provinsi telah mengimplementasikan program multi-sektoral seperti Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), gerakan Stop Panjabar (Stop Perkawinan Anak Jawa Barat), dan relawan **MOTEKAR (Motivator Ketahanan Keluarga)**yang bertugas melakukan pendampingan proaktif. Kerangka kerja ini diperkuat dengan adanya **Rencana Aksi Daerah (RKD)**untuk pencegahan perkawinan anak.
Eksploitasi Anak dan Penanganan Kelompok Rentan
Prosedur penanganan kasus eksploitasi anak, seperti anak jalanan dan pengemis, memiliki alur birokrasi yang kompleks. Kewenangan penertiban berada di tingkat Kabupaten/Kota melalui Satpol PP, yang kemudian berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat untuk asesmen dan reunifikasi. Kasus yang memerlukan penanganan panti akan dilimpahkan ke Dinas Sosial Provinsi. Kompleksitas di lapangan diilustrasikan melalui studi kasus yang dipaparkan oleh UPTD PPA, yang melibatkan dua anak balita yang dieksploitasi oleh orang tua mereka yang diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan tidak memiliki dokumen kependudukan. Proses evakuasi anak memerlukan kolaborasi lintas sektor (Camat, Kades, Polsek) dan tidak dapat dilakukan secara paksa. Setelah berhasil dilindungi, UPTD PPA harus menyerahkan anak-anak tersebut ke Dinas Sosial Provinsi karena keterbatasan mandat, khususnya ketiadaan layanan pendidikan. Isu ini juga menyasar kelompok yang lebih rentan seperti anak penyandang disabilitas intelektual, yang sering menjadi korban kekerasan seksual.
Prosedur Pengangkatan Anak dan Tantangan Adopsi Ilegal
Proses pengangkatan anak (adopsi) diatur secara ketat melalui dua mekanisme: pengangkatan langsung (biasanya antar kerabat) dan melalui lembaga. Di Jawa Barat, hanya terdapat dua lembaga yang memiliki izin resmi dari kementerian untuk menyelenggarakan adopsi, yaitu Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda(swasta) dan UPTD Geria Anak dan Balita di Batu Nunggal(pemerintah). Persyaratan bagi anak yang akan diadopsi adalah berusia di bawah 18 tahun dan berstatus terlantar atau memerlukan perlindungan khusus. Sementara itu, calon orang tua angkat harus memenuhi kriteria ketat, antara lain usia minimal 30 dan maksimal 55 tahun, status perkawinan sah minimal 5 tahun, serta lolos serangkaian pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani (termasuk tes MMPI). Di luar jalur formal, praktik adopsi informal yang diistilahkan “ngukut budak” masih marak terjadi. Praktik ini, meskipun sering didasari niat baik, secara hukum dianggap ilegal karena melanggar hak fundamental anak untuk mengetahui asal-usulnya (nasab) dan menimbulkan risiko penelantaran di kemudian hari.
Kapasitas Kelembagaan dan Kendala Sistemik
Dalam penanganan anak yang memerlukan perlindungan, Dinas Sosial mengidentifikasi sekitar 80.000 hingga 90.000 anak yang membutuhkan layanan, sementara kapasitas panti asuhan pemerintah dan swasta masih terbatas. Terdapat 1.107 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terdaftar di provinsi, dengan 407 di antaranya berfokus pada anak. Sebagai respons terhadap amanat UU TPKS, 17 dari 27 kabupaten/kota telah membentuk UPTD PPA yang berfungsi sebagai koordinator layanan terpadu, termasuk penyediaan rumah aman (safe house).Namun, tantangan operasional ini diperparah oleh kendala sistemik yang lebih besar, yaitu kebijakan efisiensi anggaran. Narasumber secara eksplisit menyatakan bahwa anggaran operasional, termasuk biaya perjalanan dinas untuk menjemput korban di lokasi, telah dihapuskan atau “dinolkan”. Kebijakan ini secara langsung melumpuhkan kemampuan lembaga seperti UPTD PPA untuk merespons kasus secara cepat dan efektif. Kondisi serupa juga dialami oleh lembaga lain, termasuk DPD RI, yang mengalami pemotongan anggaran signifikan. Konsekuensinya, kapasitas untuk melakukan fungsi pengawasan dan intervensi lapangan menjadi sangat terbatas.
Selain itu, terdapat kesulitan dalam pengembangan infrastruktur vital seperti panti sosial. Alokasi anggaran yang ada seringkali tidak dapat terserap optimal karena kendala birokrasi dan waktu. Proses seperti tender, penyusunan Detail Engineering Design (DED), dan pelaksanaan konstruksi yang memakan waktu seringkali tidak sesuai dengan siklus anggaran tahunan, sehingga dana berisiko harus dikembalikan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kebutuhan mendesak di lapangan dengan rigiditas prosedur penganggaran pemerintah. Sebagai kesimpulan, sistem perlindungan anak di Jawa Barat dihadapkan pada tantangan multidimensional. Di satu sisi, terdapat alur birokrasi dan yurisdiksi antar-lembaga yang kompleks. Di sisi lain, kendala paling fundamental adalah pemotongan anggaran yang drastis, yang secara langsung menghambat kapasitas operasional lembaga-lembaga kunci. Tanpa sumber daya yang memadai untuk operasional lapangan dan pengembangan infrastruktur, fungsi perlindungan tidak dapat berjalan optimal. Diperlukan advokasi kebijakan yang kuat untuk memastikan alokasi anggaran yang memadai serta mendorong sinergi yang lebih efektif antar-lembaga terkait untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi kelompok rentan.