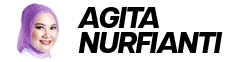Pertemuan resmi yang berlangsung di Kantor DPD RI perwakilan Jawa Barat dipandu oleh Herman Hermawan (Kepala Kantor DPD Jawa Barat) dan berfokus pada pengawasan implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dengan penekanan pada pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal di kawasan Bandung Raya.
Dalam forum ini, Agita Nurfianti (anggota DPD RI asal Jawa Barat periode 2024–2029) bertugas menyerap masukan teknis untuk dibawa ke rapat di Jakarta, selaras dengan penugasannya di Komite III DPD RI yang meliputi isu perempuan dan anak, kesehatan, pendidikan, haji dan keagamaan, pemuda dan olahraga, serta pariwisata. Agenda diskusi diarahkan pada evaluasi UU 10/2009, kondisi aktual sektor, strategi peningkatan kinerja, serta penataan tata kelola lintas wilayah di Bandung Raya.
Paparan substantif disampaikan oleh perwakilan Dinas Kebudayaan/Pariwisata Kota Bandung (selanjutnya disebut Narasumber Dinas), yang memposisikan Bandung sebagai destinasi kreatif dengan keterbatasan wisata alam akibat luas wilayah sekitar 16.000 hektare dan karakter urban yang mengandalkan wisata buatan, heritage, seni, budaya, dan kuliner.
Implementasi UU 10/2009 dijadikan dasar penyusunan rencana pembangunan kepariwisataan daerah (RIPARDA), penguatan daya tarik berbasis budaya-kreativitas, peningkatan aksesibilitas, dan pengelolaan berkelanjutan. Kriteria destinasi unggulan mencakup keunikan daya tarik dan nilai jual, aksesibilitas, infrastruktur pendukung, kesiapan masyarakat dan ekosistem pariwisata, serta kontribusi ekonomi daerah.
Sejak 2017 Bandung membangun branding sebagai “destinasi wisata kreatif”, dengan program revitalisasi kawasan heritage (koridor kolonial di pusat kota seperti Jalan Braga), pengembangan Kampung Wisata Kreatif (KWK, saat ini delapan kawasan), digitalisasi promosi, pelatihan pemandu dan SDM pariwisata, pemberdayaan UMKM, dan pembentukan Pokdarwis.
Kemitraan dengan sektor swasta difasilitasi melalui skema public–private partnership untuk proyek wisata, promosi bersama industri kreatif dan media digital, serta penyelenggaraan event skala nasional-internasional.
Dampak fiskal dilaporkan berupa peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Bandung dari sekitar 33% ke 37,1% pada 2024, terutama dari pajak restoran dan retribusi objek wisata; nilai Rp889.897 miliar disebut dalam paparan namun memerlukan verifikasi mengingat skala PAD kota.
Dinamika pasca COVID-19 mencakup efisiensi pelaku usaha dan penurunan okupansi di Desember 2024, dengan catatan pergeseran perilaku wisatawan yang “numpang makan” lalu kembali menggunakan moda cepat (WHOOSH), sehingga length of stay melemah.
Dalam kerangka kawasan, Narasumber Dinas menekankan bahwa Bandung idealnya diposisikan sebagai etalase Jawa Barat, menyerupai praktik Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengintegrasikan kota dan kabupaten (Bantul, Kulon Progo, Sleman) dalam satu ekosistem destinasi. Ia menyoroti kebutuhan konsolidasi “Bandung Raya” (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi) untuk menghindari fragmentasi dan kompetisi tidak produktif lintas wilayah administratif, karena persepsi wisatawan “ke Bandung” lazimnya bersifat fungsional lintas batas.
Secara operasional, data kunjungan 2020–2024 dihimpun dari sumber multisaluran (bandara, kereta, bus, terminal, tol), dengan perbandingan terhadap Kota Jogja yang mencapai sekitar 9,5 juta kunjungan, dan Bandung “beda tipis” pada skala kota.
Struktur usaha pariwisata Kota Bandung mencatat penginapan non-bintang berizin (“Hotel Melati”), 33 destinasi pada 2025 termasuk KWK, 243 hiburan (ditutup selama Ramadan), dan lebih dari 7.000 pelaku kuliner; asosiasi AKAR (kafe-restoran) beranggotakan sekitar 140–400 dari ribuan pelaku, menunjukkan tantangan kelembagaan.
Di sisi program, KWK mencakup Braga (Braga Bebas Kendaraan akhir pekan), Cigadung (batik Komar/Hasan dan ekosistem kreatif termasuk Café Rosin), Rajut Binong Jati (orientasi pasar ekspor ke Amerika, paket kunjungan-belanja), Literasi Cinambo (minat baca, kendala anggaran), Cigondewah (sentra kain), Pasir Kunci (aset Disbudpar dengan potensi lembah dan atraksi budaya, disarankan dikelola swasta karena keterbatasan kapasitas UPT), Sepatu Cibaduyut (tertekan produk impor, isu revitalisasi ikon sepatu pantofel hitam pasca flyover), serta kawasan terpadu Gedebage (Summarecon, Stadion GBLA, Masjid Al-Jabbar, pelestarian habitat burung “Blokok” melalui danau retensi).
Tantangan utama menyangkut aksesibilitas, kapasitas jalan dan parkir, konflik lahan komersial (contoh ruko di koridor Jalan Ibrahim Adjie), dan perizinan event yang dinilai berat.
Paparan teknis dari akademisi UPI Bandung (Dali, selanjutnya disebut Narasumber Akademik) memperdalam kerangka UU 10/2009, khususnya Pasal 7 tentang empat pilar: industri, destinasi, pemasaran, kelembagaan. Ia menginventarisasi organisasi usaha dan profesi (PHRI, ASITA, HPI, ASPI, ITLA) yang terkonsentrasi di Bandung, sementara daerah lain seperti Sumedang, Cirebon, Tasikmalaya, Subang relatif lemah.
Pada aspek destinasi, ia menegaskan definisi fungsional yang tidak identik dengan batas administratif, menyoroti kasus Tangkuban Parahu (diasosiasikan dengan Bandung, padahal administratif Subang) dan konten “hidden gem Kota Bandung” yang faktanya berada di Kabupaten Bandung Barat (Cikole).
Ketiadaan Destination Management Organization (DMO) lintas-kabupaten/kota untuk Bandung Raya menyebabkan fragmentasi pengelolaan dan pemasaran; dinas kota tidak dapat memasarkan atraksi luar yurisdiksi (misalnya Situ Patenggang), sehingga strategi promosi menjadi kaku.
Ia membandingkan model Indonesia yang bergantung pada anggaran pemerintah dengan praktik public–private partnership sejajar di negara lain, di mana asosiasi industri ikut menanggung promosi, dan mencatat periode sekitar 2015 ketika Badan Promosi Pariwisata Jawa Barat tidak berjalan optimal.
Pada aspek kelembagaan, ketiadaan entitas pengelola destinasi lintas wilayah (“tidak ada Gubernur Bandung Raya”) menyulitkan perumusan tema dan positioning kawasan. Narasumber Akademik juga mengangkat isu amenitas mikro yang memengaruhi kenyamanan, seperti pengamen dan parkir liar di ruang publik Kota Bandung, yang berulang menjadi sorotan media.
Paparan pelaku industri dari ASITA (Herman dan rekan-rekan asosiasi, selanjutnya disebut Narasumber Industri) menekankan strategi inbound, dinamika pasar regional, serta masalah operasional di lapangan.
Ia menggarisbawahi peluang yang lahir dari hadirnya kereta cepat WHOOSH; laporan operator menyebut sekitar 15% penumpang adalah wisatawan, dengan dominasi pasar Malaysia, Singapura, dan Brunei.
Namun integrasi moda masih lemah, bus belum terkoneksi langsung ke bandara, sehingga biaya tambahan muncul dan ada risiko wisatawan “lari” ke koridor lain jika konektivitas antarkota makin lancar tanpa penguatan destinasi lokal.
Narasumber Industri mengusulkan fasilitasi promosi ke negara tetangga, mencontohkan dukungan Dinas Provinsi sekitar Rp550 juta untuk promosi di Malaysia yang menghasilkan devisa/PAD sekitar Rp1,9 miliar dalam tiga hari—menunjukkan efektivitas penjualan langsung dibanding sekadar gelar budaya.
Ia memaparkan segmen minat khusus yang potensial: kayaking di danau, camper van/motorhome premium (contoh 21 unit yang tinggal 5 hari 4 malam di Jawa Barat dan total 2 bulan di Indonesia; tahun berikutnya direncanakan 35 unit), komunitas motor, serta study tour pelajar dari negara tetangga dengan kurasi konten edukatif di situs-situs makam korban Perang Dunia II (Menteng Pulo, TPU Pandu Bandung, Kerkhof Cimahi) untuk pesan moral perdamaian.
Dalam lanskap kompetitif, Malaysia dan Singapura diposisikan sebagai mitra-hub konektivitas, sementara kompetitor utama adalah Vietnam, Thailand, dan Filipina (marine tourism), dengan catatan kekuatan budaya Indonesia yang jauh lebih variatif namun kalah dalam konektivitas, kemudahan investasi, dan kenyamanan.
Ia juga menyoroti maraknya travel agent bodong, akomodasi tak resmi (kos, homestay, vila) melalui platform seperti Airbnb/OYO yang tidak tertib pajak, serta destinasi yang belum memenuhi standar perizinan (AMDAL), sehingga meminta penertiban dan kepastian hukum demi fairness fiskal dan legal.
Pada isu kebijakan study tour, Narasumber Industri dan Narasumber Akademik mengulas empat problem utama yang membentuk sentimen publik: beban biaya orang tua, praktik pungli/cashback (contoh paket Rp1.000.000 dengan cashback Rp300.000), dominasi rekreasi atas aspek edukasi, dan lemahnya keselamatan (kualitas bus, aktivitas berisiko di pantai, pengawasan).
Narasumber Akademik menilai masalah-masalah ini dapat dipecahkan spesifik per-sektor melalui pertemuan formal, alih-alih kebijakan reaktif tanpa landasan tertulis yang menimbulkan efek gentar di sekolah dan pelaku industri; ia juga menyinggung bahwa pernyataan larangan ke luar Jawa Barat belum diikuti surat edaran baru, sementara preseden sanksi terhadap kepala sekolah memicu kebingungan kebijakan.
Dalam menanggapi hal ini, Agita Nurfianti mendorong desain study tour berbiaya terjangkau dengan pemanfaatan destinasi edukatif di Bandung dan Jawa Barat, integrasi kurikulum dan tata kelola keselamatan, serta penertiban praktik diskon/cashback yang mengorbankan kualitas layanan.
Ia juga mengusulkan aktivasi UMKM di simpul transportasi seperti Stasiun Tegaluar WHOOSH (Kabupaten Bandung), memperluas komoditas dari makanan ke suvenir khas sebagai oleh-oleh, dengan kolaborasi lintas wilayah (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat). Untuk mengurangi kemacetan di koridor destinasi seperti Jalan Riau, ia mengajukan skema park-and-walk dengan sentra parkir terpusat agar beban lalu lintas di titik rawan berkurang.
Isu operasional kritis di lapangan yang mendapat penekanan adalah fenomena “pengamen dadakan” yang naik ke bus wisata di titik-titik macet, beroperasi tanpa izin dan berkoordinasi melalui grup WhatsApp, yang berbeda dari pengamen profesional di kafe/venue.
Narasumber Industri menegaskan keresahan wisatawan dan pemandu, serta menyebut tarif parkir bus di Bandung yang rata-rata Rp150.000 (bus besar) dan Rp100.000 (bus kecil) per titik, yang mengakumulasi biaya signifikan bila mengunjungi banyak destinasi.
Ia juga mengkritik homogenisasi wahana lintas destinasi (misalnya Flying Fox berulang dari Lembang hingga Ciwidey), dan lemahnya diferensiasi cinderamata antar kawasan—meski mengakui popularitas kaos “Bandung Oe” di Pasar Baru bagi wisatawan Malaysia.
Agita Nurfianti menyatakan komitmen untuk mengoordinasikan penertiban pengamen jalanan dengan Satpol PP dan Dinas Sosial, termasuk penanganan pelecehan verbal yang dilaporkan, memperkuat identitas cinderamata khas Jawa Barat, dan mendorong kurasi wahana yang menambah diferensiasi pengalaman.
Dimensi pariwisata alam dan tarif konservasi mendapat pembahasan tajam.
Narasumber Industri membandingkan tarif taman nasional dan kawasan konservasi di Indonesia yang dinilai tidak proporsional—antara lain dikenakan biaya untuk aktivitas memotret dan penggunaan drone hingga Rp3.000.000, serta peralihan pola tarif “per kunjungan” menjadi “per hari” yang secara akumulatif membebani wisatawan yang tinggal 3–7 hari (contoh Taman Nasional Gunung Halimun, tiket kumulatif Rp700.000–Rp1.500.000 hanya untuk akses dan keberadaan).
Ia menyatakan bahwa rezim penarifan historis dari sektor kehutanan “mengonversi” perlakuan wisatawan layaknya perambah hutan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan disinsentif promosi resmi oleh dinas/konten kreator.
Perbandingan dengan Malaysia ditunjukkan: banyak pantai gratis dan tiket taman nasional berkisar Rp5.000–Rp15.000 untuk warga lokal. Narasumber lain menegaskan bahwa tarif tinggi hanya dapat diterima jika transparan penggunaannya untuk konservasi, keamanan, dan asuransi; kritik “konversinya menjadi beton, bukan menjadi pohon” mencerminkan keraguan wisatawan asing yang sadar lingkungan terhadap outcome ekologis biaya yang dibayarkan.
Selain itu, muncul contoh destinasi kawah yang dinilai berpotensi internasional namun “paling mahal”, bahkan melampaui Bali, dan indikasi privatisasi pengelolaan atraksi yang meningkatkan harga.
Aksesibilitas udara melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB/Kertajati) diulas oleh Herman dengan penjelasan teknis: frekuensi penerbangan internasional (misal Singapura) terbatas karena kekurangan armada dan suku cadang terkait “kasus Boeing”, membuat maskapai (misal AirAsia) menghentikan layanan dan rute tersisa menjadi terbatas.
Meski ada alokasi subsidi tiket penumpang untuk 2025, pemanfaatan kurang optimal karena keterbatasan operator; demand disebut “penuh” namun supply seat tidak tersedia sehingga mobilitas wisatawan bergeser ke moda darat.
Dalam kerangka kebijakan nasional, Herman menyebut RPJMN 2025–2029 telah memasukkan pengembangan kawasan ekonomi pariwisata Bandung Raya; tindak lanjut direncanakan melalui rapat dengan Kementerian Pariwisata pada 15 April (pasca masa resesi) untuk membedah implementasi program bagi Jawa Barat.
Ia mengingatkan bahwa pada periode sebelumnya destinasi super prioritas terpusat di Jawa Tengah (Borobudur, Prambanan), sementara Jawa Barat belum memperoleh perlakuan setara. Dari sisi legislasi, ia menuturkan bahwa RUU Pariwisata merupakan inisiatif DPD, namun belum dibahas karena belum ada kesepakatan tiga lembaga (DPR, Pemerintah, DPD).
Secara keseluruhan, wawancara mengonfirmasi bahwa implementasi UU 10/2009 di Jawa Barat, khususnya Bandung Raya, menghadapi pekerjaan struktural pada empat pilar: penguatan ekosistem industri yang tertib izin dan pajak; penataan destinasi berbasis fungsi lintas batas administratif melalui DMO; reformasi pemasaran agar tidak terkunci yurisdiksi dan lebih kolaboratif; serta kelembagaan yang mampu merajut koordinasi interdaerah.
Bandung telah menempatkan diri sebagai etalase kuliner-budaya-kreatif dengan program KWK dan event unggulan (misalnya Asia Africa Festival, Bandung Orchestra Festival, Angklung Pride, Parahyangan Jazz Festival, Climist Live Festival, Zaha Festival kuliner pedas, Non-Flying Festival, lomba kereta peti sabun yang menggerakkan inovasi bengkel, Trademark Market, Festival Bakso Juara), namun tata kelola perizinan event, aksesibilitas, parkir, dan konflik lahan masih menjadi hambatan.
Strategi inbound ke pasar tetangga disokong oleh efektivitas promosi langsung dan kekuatan ekosistem akademik (UPI, ITB, UNPAD, Poltekpar), tetapi harus ditopang oleh revisi tarif konservasi yang adil, transparansi penggunaan dana untuk kelestarian, konektivitas udara yang membaik, penertiban pengamen jalanan, diferensiasi produk destinasi-cinderamata, serta kurasi study tour berorientasi edukasi dan keselamatan dengan biaya terjangkau.
Agita Nurfianti menutup dengan komitmen membawa isu-isu ini ke kementerian terkait di Jakarta, mengoordinasikan penanganan operasional (Satpol PP, Dinas Sosial), serta mendorong kolaborasi lintas wilayah untuk aktivasi UMKM di simpul transportasi seperti Stasiun Tegaluar dan penataan mobilitas perkotaan berbasis parkir terpusat.
Herman menegaskan rencana tindak lanjut pasca lebaran untuk bertemu “Pak Dedi” di Gedung Sate, menyelaraskan kebijakan daerah-pusat dalam kerangka RPJMN, dan mendorong pembahasan RUU Pariwisata yang telah diinisiasi DPD.
Dengan pendekatan terpadu yang berorientasi kualitas, keberlanjutan, dan kepastian hukum, diharapkan Bandung Raya dapat memperkuat posisinya sebagai primadona destinasi kreatif yang bukan sekadar singgah, melainkan meningkatkan length of stay, okupansi, dan kontribusi fiskal yang berkeadilan.
Pertemuan resmi di Kantor DPD RI Jawa Barat dipandu Herman Hermawan membahas pengawasan UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan dengan fokus pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal Bandung Raya.
Hadir Agita Nurfianti (Komite III DPD RI), Disbudpar Kota Bandung, akademisi UPI, dan pelaku industri (ASITA).
Sorotan utama:
RIPARDA & branding “destinasi wisata kreatif”: heritage Jalan Braga, Kampung Wisata Kreatif (KWK), event unggulan.
DMO lintas kab/kota Bandung Raya: mengatasi fragmentasi promosi & tata kelola destinasi.
Konektivitas WHOOSH & BIJB Kertajati: peluang inbound, tantangan integrasi moda & frekuensi penerbangan.
Isu operasional: akses & parkir, perizinan event, travel agent bodong, akomodasi tak tertib pajak, tarif konservasi.
Strategi pasar: promosi langsung ke Malaysia/Singapura, segmen minat khusus (kayaking, camper van, study tour edukatif).
UMKM & length of stay: aktivasi simpul transportasi (Stasiun Tegaluar), diferensiasi souvenir, kurasi wahana.
Video ini merangkum 4 pilar UU 10/2009 (industri, destinasi, pemasaran, kelembagaan) serta rencana tindak lanjut DPD RI untuk mendorong kolaborasi Bandung Raya, peningkatan PAD, dan pariwisata berkelanjutan.